Allahyarham KH. Dr. Jalaluddin Rakhmat
Pada sepuluh Ramadhan sepuluh tahun setelah kenabian. Setelah mendampingi Nabi saw dalam penjara Quraish di Lembah Abi Thalib, setelah menanggung kesengsaraan dan kelaparan, belahan nyawa Nabi saw Sayyidah Khadijah al-Kubra as, menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Sungguh telah datang kepadamu
dari tengah-tengah kamu
seorang Utusan
sangat berat hatinya melihat kamu menderita
sangat besar hasratnya melihat kamu berbahagia
Dialah Sang Pecinta dan Sang Penyayang
Bagi semua yang beriman
Jika mereka berpaling, katakan:
Cukuplah bagiku Allah
Tiada tuhan kecuali Dia
Kepada Dia aku pasrahkan diriku
Dia, Pemilik Arasy yang Agung
(QS Al-Taubah 89)
dari tengah-tengah kamu
seorang Utusan
sangat berat hatinya melihat kamu menderita
sangat besar hasratnya melihat kamu berbahagia
Dialah Sang Pecinta dan Sang Penyayang
Bagi semua yang beriman
Jika mereka berpaling, katakan:
Cukuplah bagiku Allah
Tiada tuhan kecuali Dia
Kepada Dia aku pasrahkan diriku
Dia, Pemilik Arasy yang Agung
(QS Al-Taubah 89)
Wafatnya Khadijah dan Abu Thalib.
Sepuluh tahun setelah Sang Nabi saw turun dari gua Hira di Bukit Cahaya. Ia yang semula dikenal sebagai al-Amin, yang terpercaya, sekarang dimaki-maki sebagai sang pendusta. Ia, yang dahulu dibawa Abu Thalib di hadapan Ka’bah untuk menurunkan hujan dengan wajahnya yang mulia, sekarang dituduh sebagai tukang sihir yang gila. Ia, yang selalu menyebarkan senyum kepada semua orang, sekarang dibalas dengan kemarahan dan kebencian.
Kepada kepalanya yang sering rebah dalam sujud di depan Ka’bah, orang melemparkan kotoran. Kepada wajahnya yang memancarkan kesucian, orang memuntahkan ludah dan umpatan. Ke bawah kakinya yang hanya melangkah untuk mengabdi kepada Tuhan dan melayani kemanusiaan, orang hamparkan duri dan benda-benda yang mencelakakan.
Inna ma’al ‘usri yusran. Sungguh bersama derita itu ada bahagia. Pada awan kelabu ada garis-garis perak. Jika di luar rumah ia menemyukan muka-muka yang garang dan marah, di rumah ia menemukan muka yang senantiasa ceria dan ramah. Jika di luar, ia diremukkan dan dijatuhkan, di rumah ia dikuatkan dan ditegakkan. Di dunianya yang paling kecil, ia mendapatkan sandaran hidup yang tak pernah goyah, ia mereguk minuman cinta yang selalu hangat, ia gugurkan seluruh kepedihannya dalam pelukan erat Penghulu wanita sedunia, Khadijah al-Kubra.
Pada sepuluh Ramadhan sepuluh tahun setelah kenabian. Setelah mendampingi Nabi saw dalam penjara Quraish di Lembah Abi Thalib, setelah menanggung kesengsaraan dan kelaparan, belahan nyawa Nabi saw itu menghembuskan nafasnya yang terakhir.
“Siapa pun tak mungkin menggantikan Khadijah,” katanya dengan rambut yang berguncang di atas ubun-ubun kepalanya. “Demi Allah, Allah tidak menggantikan Khadijah dengan seorang pun yang lebih baik dari dia. Dia beriman kepadaku, ketika orang banyak mendustakanku; dia berikan hartanya kepadaku, ketika orang banyak mengharamkannya, melalui dia Allah berikan kepadaku anak-anak yang tak pernah diberikan oleh siapa pun selain dia.” Ah, Khadijah juga yang memberikan kepadanya kasih sayang ketika semua orang memusuhinya. Sekarang telah pergi pendamping setia Nabi saw yang selalu menyalakan api perjuangan, ketika banyak orang berusaha memadamkannya. Telah tiada seorang istri yang mengorbankan kekayaan dan kemewahan untuk hidup miskin dan sederhana bersama suaminya.
“Kalau tidak ada harta Khadijah, tidak akan tegak agama ini,” ujarnya ketika mengenang kekasih hatinya. Ketika Khadijah menyerahkan seluruh hartanya, Nabi saw bergumam: Bimaa ukaafi Khadijah? Bagaimana aku harus membalas kebaikan Khadijah? Dalam perjalanan Mi’raj, Jibrail memperlihatkan kepada Nabi sebuah istana megah seluas pandangan mata, yang tidak pernah dilihat orang, tidak pernah didengar orang, dan tidak pernah terbetik dalam hati siapa pun; terbuat dari mutiara, di dalamnya tidak ada pusing yang melelahkan, tidak ada bising yang memekakkan.
“Wahai Jibril, untuk siapakah ini?” tanya sang Nabi saw. “Untuk Khadijah!”
“Selamat berbahagia untuk Khadijah. Allah telah membalas pengorbanannya dengan yang lebih baik,” ia bergumam. Di alam malakut, pada malam Mi’raj yang suci, dekat dengan Sidratul Muntaha, di bawah arasy yang agung, tetes-tetes air mata jatuh ke bumi, air mata cinta seorang suami.
Sayyidah Fathimah, permata hati Utusan Rabbil Alamin, mengadu kepada ayahnya, “Ya Nabi Allah, aku tidak bisa makan dan minum, sebelum engkau tanya kepada malaikat Jibril tentang ibuku.” Dari langit turun suara, “Khadijah di surga, didampingi Maryam ibu Isa dan Hajar ibu Ismail.”
Kini perempuan mulia itu telah tidak lagi berada di sampingnya. Tapi Nabi saw menemukan wewangian ruhnya, jejak-jejak kasihnya, di bumi dan di langit. Di bumi, dalam senyuman dan pelukan Ummu Abiha, qurrata ‘aini Rasuuli Rabbil A’lamin, Fathimah al-Zahra. Di langit, di antara para pemimpin perempuan soleh, sejak Asiyah bin Mazahim, Kultsum saudara Musa, sampai Hajar istri Ibrahim, sampai Maryam ibunda Isa.
As-Salaamu ‘alaiki ya Zawjata Sayyidil Mursaliin
Ketika kabut kehilangan Khadijah masih menyelimuti kalbunya, sebulan kemudian, Abu Thalib, orang tua Nabi yang ketiga, kembali ke pangkuan kasih Ilahi. Orangtuanya yang pertama, Abdullah, meninggal ketika Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Orang tuanya yang kedua, Abdul Muthalib, mengambil cucunya yang yatim piatu itu dan memuliakannya dalam limpahan kasihnya. Abdul Muthalib, penghulu para bangsawan Quraisy, mempunyai tempat yang khusus di Ka’bah. Dalam lindungan Ka’bah dihamparkan permadani, tidak ada yang berani duduk di atasnya kecuali Abdul Muthalib. Pada suatu hari, anak cucunya berkumpul berkeliling sekitar permadani itu, menunggu kedatangan Abdul Muthalib. Tidak lama datanglah kakeknya yang berwibawa itu melangkahkan kakinya menuju karpet istimewanya. Tiba-tiba, orang-orang melihat ada kaki-kaki kecil yang berlari dan segera duduk pada karpet kebesaran itu. Orang-orang dewasa berusaha memindahkannya ke tempat lain dan ingin mengajarinya bahwa anak kecil tidak boleh duduk di karpet pemimpin para sayyid. Tapi dengarlah suara yang berwibawa menegur mereka:
“Biarkan anakku. Demi Allah, sungguh dia akan menjadi manusia besar. Aku melihat suatu hari ia akan datang kepada kalian sebagai pemimpin kalian. Sungguh, aku melihatnya sebagai pemimpin besar yang bakal memimpin manusia.” Abdul Muthalib mengambil Muhammad kecil, menggendongnya, meletakkannya di tempat duduknya, membelai punggungnya dan menciuminya. Kedengaran ia berkata dengan lembut, “Aku belum pernah mendapat ciuman yang lebih wangi dan lebih suci dari ciumannya, belum pernah menyentuh tubuh yang lebih lembut dan lebih semerbak dari tubuhnya.” Ia menoleh kepada Abu Thalib dan berkata, lebih tepat dikatakan berwasiat: Ya Aba Thalib, Anak ini akan menduduki kedudukan yang agung, inna lihadzal ghulam sya’nan ‘azhiman. Jagalah ia sebaik-baiknya, peliharalah ia selama-lamanya. Ia sekarang sebatang kara. Jadilah kamu seperti ibunya. Jangan biarkan sesuatu yang tidak ia sukai mengenainya.” Abdul Muthalib berdiri lagi, meletakkan Muhammad kecil di atas pundaknya, dan membawanya tawaf tujuh kali putaran.
Pada hari yang lain, pada detik-detik terakhir hidupnya, dalam pembaringan sakratul mautnya, dengan Muhammad kecil dalam pelukannya, ia memanggil Abu Thalib. Air mata mengaliri pipi tuanya, membasahi janggutnya, “Ya Aba Thalib, perhatikan selalu penjagaan anak sebatang kara ini; anak yang tidak pernah mencium wangi bapaknya, dan tidak pernah cukup mereguk kasih ibunya. Perhatikan hai Abu Thalib agar kau jadikan ia seperti hatimu dalam tubuhmu. Aku khususkan yatim piatu ini dari seluruh cucuku yang lain dan aku wasiatkan ia kepadamu, karena engkau seibu dengan ayahnya. Hai Abu Thalib, kalau usiamu mencapai hari-harinya yang akan datang, ketahuilah aku adalah yang paling tahu dan paling mengerti keadaannya. Jika kamu sanggup mengikutinya, ikutilah dia, belalah dia dengan lidahmu, dengan tanganmu, dengan apa pun yang kaumiliki. Demi Allah, ia akan memimpin kalian, ia akan memiliki apa yang tidak pernah dimiliki siapa pun dari keturunan kakek-kakekku. Hai Abu Thalib, tidak pernah aku ketahui di antara kakek-kakek kita yang ditinggalkan ayah bundanya seperti ia ditinggalkan oleh kedua orangtuanya. Jagalah kesendiriannya. Apakah engkau menerima wasiatku? Abu Thalib menjawab: Saya terima wasiatmu, ayahku! Demi Allah, aku bersaksi dengan wasiat ini. Abdul Muthalib berkata: Julurkan tanganmu. Kedua tangan bertemu. Abdul Muthalib memegangnya erat-erat. Dalam suara parau ia berkata, “Sekarang maut terasa ringan bagiku,” gumamnya, sambil tidak henti-hentinya menciumi Muhammad kecil, yang waktu itu berusia delapan tahun. “Aku bersaksi aku tidak pernah menciumi seorang pun di antara anak cucuku yang harumnya sewangi dia dan wajahnya seindah dia.” Dengan kata-kata terakhir itu, berangkatlah kakek yang paling penyayang menemui Kekasih abadi.
Sejak itu Abu Thalib memeluknya erat-erat dan tidak pernah meninggalkannya siang dan malam. Ia selalu tidur bersamanya. Abu Thalib tidak mempercayai siapa pun untuk menjaganya. [1] Ketika Abu Thalib mau berdagang ke negeri jauh, ia bermaksud meninggalkan Ahmad. Perjalanan jauh menembus panas sahara di siang hari dan dingin padang pasir di malam hari dapat menyakiti fisik anak kecil yang masih lemah. Ia ingin memenuhi wasiat ayahnya -Jangan biarkan sesuatu yang tidak ia sukai mengenainya! Ia sudah meloncat ke punggung untanya. Unta sudah mendongak, pertanda bersiap berangkat. Tiba-tiba kedua telapak tangan yang lembut memegang ujung kendali untanya. Abu Thalib memandang anak yatim -yang tidak pernah ditinggalkannya- itu dengan iba. “Aku ingat bapaknya. Tak bisa kutahan deras air mataku,” ujar Abu Thalib kelak ketika ia menceritakan peristiwa itu.[2]
Waktu itu usia putra Abdullah baru delapan tahun. Keberangkatan Abu Thalib ke Syam jatuh pada musim panas dengan udara panas yang menyengat. Orang-orang Quraisy datang menemui Abu Thalib: Apa yang akan engkau lakukan pada Muhammad dan kepada siapa akan kautitipkan dia?
“Aku tidak akan menitipkannya pada siapa pun. Aku ingin ia selalu bersamaku”
“Anak kecil pada musim panas seperti ini? Kaubawa dia bersamamu”
“Demi Allah, ia tidak akan berpisah denganku ke mana pun aku pergi.”
Setia kepada wasiat Abdul Muthalib, ayahnya almarhum, Abu Thalib mengawal unta Muhammad kecil yang selalu mendahului semua unta dalam kafilah. Mari kita dengarkan lagi kisah perjalanan itu dari lidah Abu Thalib sendiri:
“Ketika kami mendekati perkampungan Bushra di Syam, tiba-tiba kami lihat gereja bergerak mendekati kami, seperti bintang yang berjalan cepat. Di tengah-tengah kami gereja itu berhenti. Bersama dia ada seorang rahib. Dia terpesona melihat awan yang selalu menemani Muhammad. Rahib itu tidak pernah bicara dengan manusia, tidak mengenal kafilah dan apa yang dibawanya. Tapi dia mengenal Nabi. Aku mendengarnya berkata: Jika dia itu dia maka engkau itu pasti engkau. Lalu kami turun dari tunggangan kami di bawah pohon besar yang dekat berdirinya rahib. Pohon itu tidak banyak cabangnya dan tidak ada buahnya. Ketika Nabi turun berguncanglah pohon itu dan menjatuhkan tiga macam buah-buahan: dua macam buah-buahan musim panas dan satu macam buah-buahan musim dingin. Semua orang takjub menyaksikannya. Ketika Bahira, rahib tadi, menyaksikan itu semua, ia berlari ke rumahnya dan mengambil makan secukupnya. Ia mendekati Nabi.
Kemudian ia meminta izin kepadaku: Bolehkah aku mengantarkan makanan itu baginya supaya ia memakannya. Aku berkata kepadanya: Dekatkan makanan itu kepadanya, walaupun ia tampak tidak menyukainya. Abu Thalib menengok kepada Nabi: Ada orang yang ingin menghormatimu dengan makanan. Makanlah! Nabi berkata: Makanan itu hanya untukku dan tidak untuk sahabat-sahabatku. Kata Bahira: Memang ini hanya untukkmu saja. Kata Nabi: Aku tidak mau makan kalau mereka tidak makan.
“Tapi aku tidak punya lebih dari itu”
“Apakah Tuan izinkan, ya Bahira, mereka makan bersamaku!”
“Tentu saja”
“Ucapkan Bismillah,” kata Nabi saw.
Ia makan dan kami pun makan. Demi Allah, waktu itu ada seratus tujuh puluh orang. Setiap orang makan dengan kenyang. Sementara itu, rahib itu duduk di dekat Nabi menjaganya sambil terpesona menyaksikan sebegitu banyak orang dan sebegitu sedikit makanan yang tersedia. Setiap saat rahib itu tidak henti-hentinya menciumi Muhammad kecil, meniupinya dengan hembusan mulutnya, sambil tidak henti-hentinya berkata: Demi Tuhannya al-Masih, orang-orang tidak tahu kebesaran anak ini.”
Bahira kemudian bertanya kepada Muhammad: Wahai anakku, aku tanyakan kepadamu tiga perkara, demi Lata dan Uzza jawablah pertanyaanku? Nabi murka ketika disebut Latta dan Uzza. Jangan tanya aku demi mereka, karena aku, demi Allah tidak ada satu pun yang aku benci seperti aku benci kepada keduanya. Keduanya adalah berhala kaumku yang terbuat dari batu. “Ini satu,” kata Bahira. “Kalau begitu, demi Allah ceritakan kepadaku” Nabi berkata: Tanyakan apa yang terbetik dalam hatimu, demi Tuhanku dan Tuhanmu yang tidak ada yang menyamainya apa pun. “Aku tanya tidur dan bangunmu.” Berceritalah Nabi tentang makan dan minumnya, bangun dan tidurnya dan segala perilaku sehari-harinya. Berita itu sangat sesuai dengan apa yang diketahui Bahira. Ia pun merebahkan dirinya menciumi kaki-kaki Muhammad:
“Duhai anakku. Betapa harum dan semerbaknya wewangianmu. Wahai Nabi yang paling banyak pengikutnya, wahai dia yang gemerlap cahayanya memenuhi dunia, wahai dia yang sebutan namanya memakmurkan mesjid, seakan-akan telah kulihat kumpulan pasukanmu dan barisan kudanya, lalu orang Arab dan Ajam ikut di belakang kamu, dengan sukarela atau terpaksa. Seakan-akan telah kulihat engkau runtuhkan Lata dan Uzza. Sehingga selainmu tidak ada yang memiliki rumah antik ini. Engkaulah yang memberikan kuncinya pada siapa pun yang kaukehendaki.
Betapa banyaknya jagoan Quraisy dan Arab yang engkau tumbangkan. Padamu ada kunci surga dan neraka. Bersamamu ada sembelihan agung dan kehancuran berhala. Engkaulah dia yang tidak terjadi hari kiamat sebelum kerajaan-kerajaan masuk semuanya ke dalam agamamu.
Tidak henti-hentinya rahib itu menciumi kedua tangan dan kedua kaki Nabi: Engkaulah doa Ibrahim dan kabar gembira dari Isa. Engkaulah yang disucikan dan dikuduskan dari segala kotoran jahiliah. Kemudian rahib menoleh kepada Abu Thalib: Aku lihat kamu tidak pernah berpisah darinya. Bagaimana hubungan dia dengan kamu. “Dia anakku,” kata Abu Thalib. Tak mungkin dia anakmu. Karena tertulis bahwa anak ini tidak punya orangtua yang masih hidup. “Dia keponakanku. Ayahnya telah meninggal dunia ketika ia dalam kandungan ibunya. Ibunya meninggal ketika ia berusia enam tahun. “Benar itulah dia. Aku minta engkau bawa dia kembali ke negerinya, karena di atas bumi ini tidak ada Yahudi, Nashrani atau pemilik Kitab suci yang tidak mengetahui kelahirannya sebagaimana aku mengenalnya.
Ketika Abu Thalib beserta rombongan mau meninggalkan Bahira, ia menangis dengan tangisan yang berat: Wahai putra Aminah, aku sudah melihat orang-orang Arab melepaskan anak panahnya padamu, karib kerabat memutuskan persaudarannya darimu. Kemudian ia berpaling kepada Abu Thalib: Engkau, wahai paman, jagalah kekeluargaan yang sudah tersambung erat, jagalah wasiat ayahmu. Orang-orang Quraisy pasti akan menjauhimu. Aku tahu engkau tidak menampakkan imanmu secara lahir tetapi engkau beriman kepadanya dalam lubuk hatimu. Tetapi salah seorang anakmu akan menjadi penolongnya yang tangguh. Namanya termaktub di langit sebagai Pahlawan Sang Singa, di bumi sebagai Sang Gagah Berani. Dari padanya akan lahir dua orang pemuda yang syahid. Dialah penghulu Arab dan pemimpinnya. Dia lebih mengenal kitab dari sahabat-sahabat Isa.”
Apa yang dilihat Bahira semuanya terjadi. Dalam gelombang keras yang menghantam Nabi, Abu Thalib bersama anaknya Sang Singa tegak berdiri seperti tembok baja. Pada suatu hari serombongan orang Quraisy menemui Abu Thalib: Hai Abu Thalib, keponakanmu telah menistakan tuhan-tuhan kami, mengejek agama kami, merendahkan pikiran kami, menganggap sesat orangtua-orang tua kami, sekarang buatlah keputusan. Apakah engkau akan menyuruhnya berhenti atau engkau membiarkan kami untuk bertindak terhadapnya?
Setelah itu, Abu Thalib memanggil Nabi dan menceritakan pembicaraan tokoh-tokoh Quraisy kepadanya. Ia berkata: Ikut aku atau ikut dirimu. Jangan bebankan aku dengan beban yang tidak sanggup aku pikul. Inilah jawaban Nabi, jawaban yang menunjukkan kekuatan keyakinannya, keteguhan pendiriannya, dan ketegaran hatinya:
Demi Allah, wahai pamanku, sekiranya mereka letakkan matahari di tanganku dan rembulan di tangan kiriku agar aku menghentikan perjuangan ini, aku tidak akan berhenti sampai Allah memberikan kemenangan kepadaku atau aku binasa di dalamnya. Nabi bangkit untuk meninggalkan rumah pamannya. Abu Thalib sontak meloncat dan memanggil Nabi:
Demi Allah aku tidak akan menyerahkan kamu kepada siapa pun selama-lamanya. Paman yang pandai memainkan pedang dan bahasa kemudian melantunkan puisi: [3]
Sepuluh tahun setelah Sang Nabi saw turun dari gua Hira di Bukit Cahaya. Ia yang semula dikenal sebagai al-Amin, yang terpercaya, sekarang dimaki-maki sebagai sang pendusta. Ia, yang dahulu dibawa Abu Thalib di hadapan Ka’bah untuk menurunkan hujan dengan wajahnya yang mulia, sekarang dituduh sebagai tukang sihir yang gila. Ia, yang selalu menyebarkan senyum kepada semua orang, sekarang dibalas dengan kemarahan dan kebencian.
Kepada kepalanya yang sering rebah dalam sujud di depan Ka’bah, orang melemparkan kotoran. Kepada wajahnya yang memancarkan kesucian, orang memuntahkan ludah dan umpatan. Ke bawah kakinya yang hanya melangkah untuk mengabdi kepada Tuhan dan melayani kemanusiaan, orang hamparkan duri dan benda-benda yang mencelakakan.
Inna ma’al ‘usri yusran. Sungguh bersama derita itu ada bahagia. Pada awan kelabu ada garis-garis perak. Jika di luar rumah ia menemyukan muka-muka yang garang dan marah, di rumah ia menemukan muka yang senantiasa ceria dan ramah. Jika di luar, ia diremukkan dan dijatuhkan, di rumah ia dikuatkan dan ditegakkan. Di dunianya yang paling kecil, ia mendapatkan sandaran hidup yang tak pernah goyah, ia mereguk minuman cinta yang selalu hangat, ia gugurkan seluruh kepedihannya dalam pelukan erat Penghulu wanita sedunia, Khadijah al-Kubra.
Pada sepuluh Ramadhan sepuluh tahun setelah kenabian. Setelah mendampingi Nabi saw dalam penjara Quraish di Lembah Abi Thalib, setelah menanggung kesengsaraan dan kelaparan, belahan nyawa Nabi saw itu menghembuskan nafasnya yang terakhir.
“Siapa pun tak mungkin menggantikan Khadijah,” katanya dengan rambut yang berguncang di atas ubun-ubun kepalanya. “Demi Allah, Allah tidak menggantikan Khadijah dengan seorang pun yang lebih baik dari dia. Dia beriman kepadaku, ketika orang banyak mendustakanku; dia berikan hartanya kepadaku, ketika orang banyak mengharamkannya, melalui dia Allah berikan kepadaku anak-anak yang tak pernah diberikan oleh siapa pun selain dia.” Ah, Khadijah juga yang memberikan kepadanya kasih sayang ketika semua orang memusuhinya. Sekarang telah pergi pendamping setia Nabi saw yang selalu menyalakan api perjuangan, ketika banyak orang berusaha memadamkannya. Telah tiada seorang istri yang mengorbankan kekayaan dan kemewahan untuk hidup miskin dan sederhana bersama suaminya.
“Kalau tidak ada harta Khadijah, tidak akan tegak agama ini,” ujarnya ketika mengenang kekasih hatinya. Ketika Khadijah menyerahkan seluruh hartanya, Nabi saw bergumam: Bimaa ukaafi Khadijah? Bagaimana aku harus membalas kebaikan Khadijah? Dalam perjalanan Mi’raj, Jibrail memperlihatkan kepada Nabi sebuah istana megah seluas pandangan mata, yang tidak pernah dilihat orang, tidak pernah didengar orang, dan tidak pernah terbetik dalam hati siapa pun; terbuat dari mutiara, di dalamnya tidak ada pusing yang melelahkan, tidak ada bising yang memekakkan.
“Wahai Jibril, untuk siapakah ini?” tanya sang Nabi saw. “Untuk Khadijah!”
“Selamat berbahagia untuk Khadijah. Allah telah membalas pengorbanannya dengan yang lebih baik,” ia bergumam. Di alam malakut, pada malam Mi’raj yang suci, dekat dengan Sidratul Muntaha, di bawah arasy yang agung, tetes-tetes air mata jatuh ke bumi, air mata cinta seorang suami.
Sayyidah Fathimah, permata hati Utusan Rabbil Alamin, mengadu kepada ayahnya, “Ya Nabi Allah, aku tidak bisa makan dan minum, sebelum engkau tanya kepada malaikat Jibril tentang ibuku.” Dari langit turun suara, “Khadijah di surga, didampingi Maryam ibu Isa dan Hajar ibu Ismail.”
Kini perempuan mulia itu telah tidak lagi berada di sampingnya. Tapi Nabi saw menemukan wewangian ruhnya, jejak-jejak kasihnya, di bumi dan di langit. Di bumi, dalam senyuman dan pelukan Ummu Abiha, qurrata ‘aini Rasuuli Rabbil A’lamin, Fathimah al-Zahra. Di langit, di antara para pemimpin perempuan soleh, sejak Asiyah bin Mazahim, Kultsum saudara Musa, sampai Hajar istri Ibrahim, sampai Maryam ibunda Isa.
As-Salaamu ‘alaiki ya Zawjata Sayyidil Mursaliin
Ketika kabut kehilangan Khadijah masih menyelimuti kalbunya, sebulan kemudian, Abu Thalib, orang tua Nabi yang ketiga, kembali ke pangkuan kasih Ilahi. Orangtuanya yang pertama, Abdullah, meninggal ketika Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Orang tuanya yang kedua, Abdul Muthalib, mengambil cucunya yang yatim piatu itu dan memuliakannya dalam limpahan kasihnya. Abdul Muthalib, penghulu para bangsawan Quraisy, mempunyai tempat yang khusus di Ka’bah. Dalam lindungan Ka’bah dihamparkan permadani, tidak ada yang berani duduk di atasnya kecuali Abdul Muthalib. Pada suatu hari, anak cucunya berkumpul berkeliling sekitar permadani itu, menunggu kedatangan Abdul Muthalib. Tidak lama datanglah kakeknya yang berwibawa itu melangkahkan kakinya menuju karpet istimewanya. Tiba-tiba, orang-orang melihat ada kaki-kaki kecil yang berlari dan segera duduk pada karpet kebesaran itu. Orang-orang dewasa berusaha memindahkannya ke tempat lain dan ingin mengajarinya bahwa anak kecil tidak boleh duduk di karpet pemimpin para sayyid. Tapi dengarlah suara yang berwibawa menegur mereka:
“Biarkan anakku. Demi Allah, sungguh dia akan menjadi manusia besar. Aku melihat suatu hari ia akan datang kepada kalian sebagai pemimpin kalian. Sungguh, aku melihatnya sebagai pemimpin besar yang bakal memimpin manusia.” Abdul Muthalib mengambil Muhammad kecil, menggendongnya, meletakkannya di tempat duduknya, membelai punggungnya dan menciuminya. Kedengaran ia berkata dengan lembut, “Aku belum pernah mendapat ciuman yang lebih wangi dan lebih suci dari ciumannya, belum pernah menyentuh tubuh yang lebih lembut dan lebih semerbak dari tubuhnya.” Ia menoleh kepada Abu Thalib dan berkata, lebih tepat dikatakan berwasiat: Ya Aba Thalib, Anak ini akan menduduki kedudukan yang agung, inna lihadzal ghulam sya’nan ‘azhiman. Jagalah ia sebaik-baiknya, peliharalah ia selama-lamanya. Ia sekarang sebatang kara. Jadilah kamu seperti ibunya. Jangan biarkan sesuatu yang tidak ia sukai mengenainya.” Abdul Muthalib berdiri lagi, meletakkan Muhammad kecil di atas pundaknya, dan membawanya tawaf tujuh kali putaran.
Pada hari yang lain, pada detik-detik terakhir hidupnya, dalam pembaringan sakratul mautnya, dengan Muhammad kecil dalam pelukannya, ia memanggil Abu Thalib. Air mata mengaliri pipi tuanya, membasahi janggutnya, “Ya Aba Thalib, perhatikan selalu penjagaan anak sebatang kara ini; anak yang tidak pernah mencium wangi bapaknya, dan tidak pernah cukup mereguk kasih ibunya. Perhatikan hai Abu Thalib agar kau jadikan ia seperti hatimu dalam tubuhmu. Aku khususkan yatim piatu ini dari seluruh cucuku yang lain dan aku wasiatkan ia kepadamu, karena engkau seibu dengan ayahnya. Hai Abu Thalib, kalau usiamu mencapai hari-harinya yang akan datang, ketahuilah aku adalah yang paling tahu dan paling mengerti keadaannya. Jika kamu sanggup mengikutinya, ikutilah dia, belalah dia dengan lidahmu, dengan tanganmu, dengan apa pun yang kaumiliki. Demi Allah, ia akan memimpin kalian, ia akan memiliki apa yang tidak pernah dimiliki siapa pun dari keturunan kakek-kakekku. Hai Abu Thalib, tidak pernah aku ketahui di antara kakek-kakek kita yang ditinggalkan ayah bundanya seperti ia ditinggalkan oleh kedua orangtuanya. Jagalah kesendiriannya. Apakah engkau menerima wasiatku? Abu Thalib menjawab: Saya terima wasiatmu, ayahku! Demi Allah, aku bersaksi dengan wasiat ini. Abdul Muthalib berkata: Julurkan tanganmu. Kedua tangan bertemu. Abdul Muthalib memegangnya erat-erat. Dalam suara parau ia berkata, “Sekarang maut terasa ringan bagiku,” gumamnya, sambil tidak henti-hentinya menciumi Muhammad kecil, yang waktu itu berusia delapan tahun. “Aku bersaksi aku tidak pernah menciumi seorang pun di antara anak cucuku yang harumnya sewangi dia dan wajahnya seindah dia.” Dengan kata-kata terakhir itu, berangkatlah kakek yang paling penyayang menemui Kekasih abadi.
Sejak itu Abu Thalib memeluknya erat-erat dan tidak pernah meninggalkannya siang dan malam. Ia selalu tidur bersamanya. Abu Thalib tidak mempercayai siapa pun untuk menjaganya. [1] Ketika Abu Thalib mau berdagang ke negeri jauh, ia bermaksud meninggalkan Ahmad. Perjalanan jauh menembus panas sahara di siang hari dan dingin padang pasir di malam hari dapat menyakiti fisik anak kecil yang masih lemah. Ia ingin memenuhi wasiat ayahnya -Jangan biarkan sesuatu yang tidak ia sukai mengenainya! Ia sudah meloncat ke punggung untanya. Unta sudah mendongak, pertanda bersiap berangkat. Tiba-tiba kedua telapak tangan yang lembut memegang ujung kendali untanya. Abu Thalib memandang anak yatim -yang tidak pernah ditinggalkannya- itu dengan iba. “Aku ingat bapaknya. Tak bisa kutahan deras air mataku,” ujar Abu Thalib kelak ketika ia menceritakan peristiwa itu.[2]
Waktu itu usia putra Abdullah baru delapan tahun. Keberangkatan Abu Thalib ke Syam jatuh pada musim panas dengan udara panas yang menyengat. Orang-orang Quraisy datang menemui Abu Thalib: Apa yang akan engkau lakukan pada Muhammad dan kepada siapa akan kautitipkan dia?
“Aku tidak akan menitipkannya pada siapa pun. Aku ingin ia selalu bersamaku”
“Anak kecil pada musim panas seperti ini? Kaubawa dia bersamamu”
“Demi Allah, ia tidak akan berpisah denganku ke mana pun aku pergi.”
Setia kepada wasiat Abdul Muthalib, ayahnya almarhum, Abu Thalib mengawal unta Muhammad kecil yang selalu mendahului semua unta dalam kafilah. Mari kita dengarkan lagi kisah perjalanan itu dari lidah Abu Thalib sendiri:
“Ketika kami mendekati perkampungan Bushra di Syam, tiba-tiba kami lihat gereja bergerak mendekati kami, seperti bintang yang berjalan cepat. Di tengah-tengah kami gereja itu berhenti. Bersama dia ada seorang rahib. Dia terpesona melihat awan yang selalu menemani Muhammad. Rahib itu tidak pernah bicara dengan manusia, tidak mengenal kafilah dan apa yang dibawanya. Tapi dia mengenal Nabi. Aku mendengarnya berkata: Jika dia itu dia maka engkau itu pasti engkau. Lalu kami turun dari tunggangan kami di bawah pohon besar yang dekat berdirinya rahib. Pohon itu tidak banyak cabangnya dan tidak ada buahnya. Ketika Nabi turun berguncanglah pohon itu dan menjatuhkan tiga macam buah-buahan: dua macam buah-buahan musim panas dan satu macam buah-buahan musim dingin. Semua orang takjub menyaksikannya. Ketika Bahira, rahib tadi, menyaksikan itu semua, ia berlari ke rumahnya dan mengambil makan secukupnya. Ia mendekati Nabi.
Kemudian ia meminta izin kepadaku: Bolehkah aku mengantarkan makanan itu baginya supaya ia memakannya. Aku berkata kepadanya: Dekatkan makanan itu kepadanya, walaupun ia tampak tidak menyukainya. Abu Thalib menengok kepada Nabi: Ada orang yang ingin menghormatimu dengan makanan. Makanlah! Nabi berkata: Makanan itu hanya untukku dan tidak untuk sahabat-sahabatku. Kata Bahira: Memang ini hanya untukkmu saja. Kata Nabi: Aku tidak mau makan kalau mereka tidak makan.
“Tapi aku tidak punya lebih dari itu”
“Apakah Tuan izinkan, ya Bahira, mereka makan bersamaku!”
“Tentu saja”
“Ucapkan Bismillah,” kata Nabi saw.
Ia makan dan kami pun makan. Demi Allah, waktu itu ada seratus tujuh puluh orang. Setiap orang makan dengan kenyang. Sementara itu, rahib itu duduk di dekat Nabi menjaganya sambil terpesona menyaksikan sebegitu banyak orang dan sebegitu sedikit makanan yang tersedia. Setiap saat rahib itu tidak henti-hentinya menciumi Muhammad kecil, meniupinya dengan hembusan mulutnya, sambil tidak henti-hentinya berkata: Demi Tuhannya al-Masih, orang-orang tidak tahu kebesaran anak ini.”
Bahira kemudian bertanya kepada Muhammad: Wahai anakku, aku tanyakan kepadamu tiga perkara, demi Lata dan Uzza jawablah pertanyaanku? Nabi murka ketika disebut Latta dan Uzza. Jangan tanya aku demi mereka, karena aku, demi Allah tidak ada satu pun yang aku benci seperti aku benci kepada keduanya. Keduanya adalah berhala kaumku yang terbuat dari batu. “Ini satu,” kata Bahira. “Kalau begitu, demi Allah ceritakan kepadaku” Nabi berkata: Tanyakan apa yang terbetik dalam hatimu, demi Tuhanku dan Tuhanmu yang tidak ada yang menyamainya apa pun. “Aku tanya tidur dan bangunmu.” Berceritalah Nabi tentang makan dan minumnya, bangun dan tidurnya dan segala perilaku sehari-harinya. Berita itu sangat sesuai dengan apa yang diketahui Bahira. Ia pun merebahkan dirinya menciumi kaki-kaki Muhammad:
“Duhai anakku. Betapa harum dan semerbaknya wewangianmu. Wahai Nabi yang paling banyak pengikutnya, wahai dia yang gemerlap cahayanya memenuhi dunia, wahai dia yang sebutan namanya memakmurkan mesjid, seakan-akan telah kulihat kumpulan pasukanmu dan barisan kudanya, lalu orang Arab dan Ajam ikut di belakang kamu, dengan sukarela atau terpaksa. Seakan-akan telah kulihat engkau runtuhkan Lata dan Uzza. Sehingga selainmu tidak ada yang memiliki rumah antik ini. Engkaulah yang memberikan kuncinya pada siapa pun yang kaukehendaki.
Betapa banyaknya jagoan Quraisy dan Arab yang engkau tumbangkan. Padamu ada kunci surga dan neraka. Bersamamu ada sembelihan agung dan kehancuran berhala. Engkaulah dia yang tidak terjadi hari kiamat sebelum kerajaan-kerajaan masuk semuanya ke dalam agamamu.
Tidak henti-hentinya rahib itu menciumi kedua tangan dan kedua kaki Nabi: Engkaulah doa Ibrahim dan kabar gembira dari Isa. Engkaulah yang disucikan dan dikuduskan dari segala kotoran jahiliah. Kemudian rahib menoleh kepada Abu Thalib: Aku lihat kamu tidak pernah berpisah darinya. Bagaimana hubungan dia dengan kamu. “Dia anakku,” kata Abu Thalib. Tak mungkin dia anakmu. Karena tertulis bahwa anak ini tidak punya orangtua yang masih hidup. “Dia keponakanku. Ayahnya telah meninggal dunia ketika ia dalam kandungan ibunya. Ibunya meninggal ketika ia berusia enam tahun. “Benar itulah dia. Aku minta engkau bawa dia kembali ke negerinya, karena di atas bumi ini tidak ada Yahudi, Nashrani atau pemilik Kitab suci yang tidak mengetahui kelahirannya sebagaimana aku mengenalnya.
Ketika Abu Thalib beserta rombongan mau meninggalkan Bahira, ia menangis dengan tangisan yang berat: Wahai putra Aminah, aku sudah melihat orang-orang Arab melepaskan anak panahnya padamu, karib kerabat memutuskan persaudarannya darimu. Kemudian ia berpaling kepada Abu Thalib: Engkau, wahai paman, jagalah kekeluargaan yang sudah tersambung erat, jagalah wasiat ayahmu. Orang-orang Quraisy pasti akan menjauhimu. Aku tahu engkau tidak menampakkan imanmu secara lahir tetapi engkau beriman kepadanya dalam lubuk hatimu. Tetapi salah seorang anakmu akan menjadi penolongnya yang tangguh. Namanya termaktub di langit sebagai Pahlawan Sang Singa, di bumi sebagai Sang Gagah Berani. Dari padanya akan lahir dua orang pemuda yang syahid. Dialah penghulu Arab dan pemimpinnya. Dia lebih mengenal kitab dari sahabat-sahabat Isa.”
Apa yang dilihat Bahira semuanya terjadi. Dalam gelombang keras yang menghantam Nabi, Abu Thalib bersama anaknya Sang Singa tegak berdiri seperti tembok baja. Pada suatu hari serombongan orang Quraisy menemui Abu Thalib: Hai Abu Thalib, keponakanmu telah menistakan tuhan-tuhan kami, mengejek agama kami, merendahkan pikiran kami, menganggap sesat orangtua-orang tua kami, sekarang buatlah keputusan. Apakah engkau akan menyuruhnya berhenti atau engkau membiarkan kami untuk bertindak terhadapnya?
Setelah itu, Abu Thalib memanggil Nabi dan menceritakan pembicaraan tokoh-tokoh Quraisy kepadanya. Ia berkata: Ikut aku atau ikut dirimu. Jangan bebankan aku dengan beban yang tidak sanggup aku pikul. Inilah jawaban Nabi, jawaban yang menunjukkan kekuatan keyakinannya, keteguhan pendiriannya, dan ketegaran hatinya:
Demi Allah, wahai pamanku, sekiranya mereka letakkan matahari di tanganku dan rembulan di tangan kiriku agar aku menghentikan perjuangan ini, aku tidak akan berhenti sampai Allah memberikan kemenangan kepadaku atau aku binasa di dalamnya. Nabi bangkit untuk meninggalkan rumah pamannya. Abu Thalib sontak meloncat dan memanggil Nabi:
Demi Allah aku tidak akan menyerahkan kamu kepada siapa pun selama-lamanya. Paman yang pandai memainkan pedang dan bahasa kemudian melantunkan puisi: [3]
Demi Allah, mereka semua tak mungkin menyentuhmu
Sampai aku berkalang kaku di kuburku
Jalankan tugas yang telah dibebankan padamu
Gembirakan dan tenangkan hatimu
Engkau memanggilku
Dan kutahu kaubicara tulus
Kau pasti benar
Karena kau terkenal sebagai Sang Terpercaya
Sungguh aku tahu agama Muhammad
agama terbaik di antara semua agama umat manusia
Sampai aku berkalang kaku di kuburku
Jalankan tugas yang telah dibebankan padamu
Gembirakan dan tenangkan hatimu
Engkau memanggilku
Dan kutahu kaubicara tulus
Kau pasti benar
Karena kau terkenal sebagai Sang Terpercaya
Sungguh aku tahu agama Muhammad
agama terbaik di antara semua agama umat manusia
Dua bulan lebih setelah keluar dari penjara di lembah yang ditetapkan oleh parlemen Quraisy, Abu Thalib jatuh sakit. Nabi yang mulia mengusap dahi Abi Thalib empat kali seraya menyapanya dengan penuh kasih: Ya ‘Ammi, kaupelihara aku pada waktu kecil, kauayomi ketika aku yatim, kaubela aku setelah dewasa. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan yang berlimpah. Segera setelah itu, ruhnya yang suci naik ke langit yang tinggi. Pada usia 86 tahun. Selang beberapa hari setelah wafat Khadijah.
Kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi berpesan, “Hai Ali, segeralah kaumandikan, kaukafani, kautaburkan hanuth. Jika sudah kauletakkan dia pada pembaringannya, beritahu aku.” Dalam rintihan pedihnya di depan jenazah paman yang dicintainya, Nabi kembali mengulangi ucapannya sebelumnya: Wahai pamanku, kauperkuat tali persaudaraan, semoga kau dapat limpahan anugrah Tuhan, kau merawat dan menjagaku sejak kecil, kau bela dan kautolong aku sesudah aku besar.” Kemudian ia hadapkan mukanya kepada orang banyak dan berkata: Sungguh, demi Allah, aku akan berikan syafaatku kepada pamanku dengan syafaat yang menakjubkan jin dan manusia. Ia menyebut Abu Thalib dengan sebutan paman. Tapi ia menyebutnya juga sebagai kaafilul yatim, pemelihara anak yatim. Tentang Abu Thaliblah Nabi berkata: Aku dan kaafilul yatim di surga seperti ini. Sambil ia tunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. (Lebih dari seribu tahun setelah itu, mayoritas pengikut Nabi memasukkan Abu Thalib ke neraka, mendapat siksaan paling ringan dengan syafaat Nabi -yakni, hanya terompah kakinya yang menyentuh neraka tetapi bergolak otak di dalam kepalanya. Paman Nabi yang malang! Hadis pemelihara anak yatim di surga bersama Nabi berlaku bagi setiap orang kecuali Abu Thalib.)
As- Salaamu ‘alaika ya ‘Amma Rasuulillah saw wa Kaafilal Yatiim
Salam bagimu, wahai Paman Rasulullah dan Pemelihara Sang Yatim
Catatan Kaki
[1] Ibn Babawaih al-Qummi, wafat 381H, Kamaal al-Diin wa Tamaam al-Ni’mah, Bab 12: Fii Khabar ‘Abd al-Muthallib wa Abii Thalib, Beirut: Muassah al-A’lami lil-Mathbuat, 1412.
[2] Lihat sumber-sumbernya pada O Muhammadku!: Puisi cinta untuk Nabi saw.
[3] Lihat sumber-sumbernya pada O’Muhammadku, ibid.
Kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi berpesan, “Hai Ali, segeralah kaumandikan, kaukafani, kautaburkan hanuth. Jika sudah kauletakkan dia pada pembaringannya, beritahu aku.” Dalam rintihan pedihnya di depan jenazah paman yang dicintainya, Nabi kembali mengulangi ucapannya sebelumnya: Wahai pamanku, kauperkuat tali persaudaraan, semoga kau dapat limpahan anugrah Tuhan, kau merawat dan menjagaku sejak kecil, kau bela dan kautolong aku sesudah aku besar.” Kemudian ia hadapkan mukanya kepada orang banyak dan berkata: Sungguh, demi Allah, aku akan berikan syafaatku kepada pamanku dengan syafaat yang menakjubkan jin dan manusia. Ia menyebut Abu Thalib dengan sebutan paman. Tapi ia menyebutnya juga sebagai kaafilul yatim, pemelihara anak yatim. Tentang Abu Thaliblah Nabi berkata: Aku dan kaafilul yatim di surga seperti ini. Sambil ia tunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. (Lebih dari seribu tahun setelah itu, mayoritas pengikut Nabi memasukkan Abu Thalib ke neraka, mendapat siksaan paling ringan dengan syafaat Nabi -yakni, hanya terompah kakinya yang menyentuh neraka tetapi bergolak otak di dalam kepalanya. Paman Nabi yang malang! Hadis pemelihara anak yatim di surga bersama Nabi berlaku bagi setiap orang kecuali Abu Thalib.)
As- Salaamu ‘alaika ya ‘Amma Rasuulillah saw wa Kaafilal Yatiim
Salam bagimu, wahai Paman Rasulullah dan Pemelihara Sang Yatim
Catatan Kaki
[1] Ibn Babawaih al-Qummi, wafat 381H, Kamaal al-Diin wa Tamaam al-Ni’mah, Bab 12: Fii Khabar ‘Abd al-Muthallib wa Abii Thalib, Beirut: Muassah al-A’lami lil-Mathbuat, 1412.
[2] Lihat sumber-sumbernya pada O Muhammadku!: Puisi cinta untuk Nabi saw.
[3] Lihat sumber-sumbernya pada O’Muhammadku, ibid.
Kunjungan


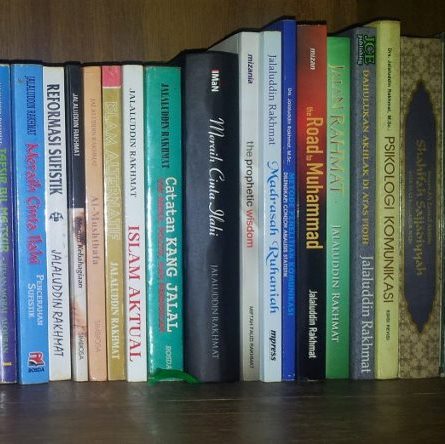
 RSS Feed
RSS Feed
