KH. Dr. Jalaluddin Rakhmat
Ketua Dewan Syura IJABI
Ketua Dewan Syura IJABI
In letzter Zeit hat ein vollkommen neuer Blick auf die menschliche Natur
an Bedeutung gewonnen, der einen entscheidenden Einfluss darauf haben
wird, wie wir in den kommenden Jahrhunderten die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umweltpolitischen Weichen stellen. Wir haben den
Homo empathicus entdeckt.
Jeremy Rifkin
Die Emphatische Zivilizatio
“Malam 24 Desember, 1914, Flanders. Perang dunia pertama memasuki bulan kedelapan. Jutaan tentara disekap parit-parit darurat yang digali sepanjang pedesaan Eropa. Di berbagai tempat para prajurit yang berlawanan membuat galian dalam jarak 45.5 meter satu sama lain, pada jarak yang masih bisa saling mendengar teriakan. Keadaan parit seperti neraka. Udara winter yang dingin masuk ke tulang sumsum. Parit-parit menjadi kubangan. Para prajurit berbagi tempat dengan tikus dan kutu. Karena tidak ada toilet yang memadai, bau kotoran manusia tercium di mana-mana. Orang tidur berdiri untuk menghindari kotoran dan lumpur dari pembuatan parit darurat. Mayat-mayat bergelimpangan di daerah tak bertuan di antara pasukan-pasukan yang berhadapan. Jenazah dibiarkan membusuk di dekat sekitar dua meter dengan teman-temannya yang masih hidup, yang tidak mampu menguburkaan mereka.”
Deangan paragraf itu, Jeremy Rifkin memulai bukunya tentang peradaban empatis. Sangat dramatis. Untuk selanjutnya saya tuliskan kembali kisah yang terkenal sebagai Perdamaian Natal, Christmas truce, Weihnachtsfrieden atau Trêve de Noël.
Malam Natal membungkus bumi, dan langit menaburkan butir-butir salju. Parit-parit perlahan-lahan dipenuhi air dan lumpur. Suasana mencekam. Seperti biasa, malam Natal mengingatkan mereka pada orang-orang yag dikasihi, yang ditinggalkan di kampung halamannya. Sebagian di antara prajurit ada yang membuka-buka surat atau hadiah Natal yang dikirimkan ke front.
Pasukan Inggris dan Perancis di Front Barat tiba-tiba dikejutkan senandung yang bermula pelan-pelan, kemudian makin lama makin keras, diikuti oleh orang yang makin lama makin banyak, dari arah pasukan Jerman. Liriknya dalam bahasa Jerman, tetapi lagunya dikenal oleh semua orang. “Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht”. Dari arah pasukan Jerman. Bibir-bibir mereka tanpa terasa menggumamkan lagu itu dengan lirik dalam bahasa masing-masing. Makin lama makin keras. Ketika mata-mata prajurit Inggris diarahkan ke lingkaran parit Jerman, mereka melihat pohon-pohon Natal kecil berkelip-kelip sepanjang lingkaran parit. “Seperti untaian tasbih,” kata seorang prajurit Inggris. Hampir tak terasa, airmata mereka mengalir membasahi pipi, menghangatkan kebekuan karena percik-percik hujan salju di muka mereka.
Dari dalam parit kedua belah pihak menyembul kepala-kepala berani. Biasanya kepala-kepala yang muncul disambut dengan tembakan sniper. Kali ini, bukan tembakan yang menyertai kepala-kepala itu, tapi kalimat Inggris dengan aksen Jerman. “Merry Xmas! Merry Xmas!” dibalas dengan kalimat yang sama oleh tentara Inggris dan Joyeux Noelle oleh tentara Perancis. Tubuh-tubuh yang kecapean sekarang sudah berada di tanah lapang tak bertuan.
“My Name is James“
“Ich heisse Otto”
Mereka berjabatan tangan, diikuti oleh ratusan, bahkan ribuan orang. Menurut Wikipedia, sekitar 100.000 tentara Inggris dan Jerman terlibat dalam gencatan senjata tidak resmi; dan tidak disetujui oleh para perwira atasan mereka. Mereka yang beberapa jam sebelumnya saling membunuh sekarang bersalaman. Muka-muka beringas sekarang menunjukkan keramahan. Mereka bernyanyi bersama, saling bercanda, bertukar hadiah, barbagi kenangan. Mereka menyanyikan Christmas Carol ketika bertemu dan sebelum berpisah mereka menyanyikan “Auld Lang Syne”
Henry Williamson, waktu itu prajurit berusia 19 tahun, menulis surat pada ibunya:
“Mama tersayang, aku menulis dari parit perang. Sekarang jam 11 pagi. Di sampingku ada pelita minyak, di depanku galian yang basah dengan jerami di dalamnya. Tanah di bawahku licin dalam parit yang sebenarnya, tetapi di mana-mana beku. Di mulutku ada pipa hadiah dari Princess Mary. Dalam pipaku ada tembakau. Tentu saja, pasti begitu kata Mama. Tapi sebentar. Dalam pipa ini ada tembakau Jerman. Haha, pasti kata Mama lagi, diambil dari tawanan Jerman atau ditemukan dari parit musuh yang direbut. Bukan, Mama sayang. Dari prajurit Jerman. Benar, prajurit Jerman dibawa dari paritnya sendiri. Kemarin orang Inggris dan orang Jerman bertemu, bersalaman di lapangan di antara parit-parit, berbagi suvenir, dan bersalaman. Ya, sepanjang hari Natal dan pada waktu aku menulis surat ini. Marvellous, isn’t it? Indah nian, bukan?”
Itulah perdamaian kecil dalam perang besar di front sebelah barat, 1914, ketika Jerman, Perancis, dan Inggris, bersama-sama merayakan Hari Natal. Kalimat barusan sebetulnya terjemahan dari judul buku yang sangat panjang ditulis Michael, Jürgs (2005), Der kleine Frieden im Großen Krieg: Westfront 1914: als Deutsche, Franzosen und Briten gemeinsam Weihnachten feierten. München.
Menurut Rifkin, perdamaian kecil ini mengungkapkan “hakikat” kemanusiaan yang selama ratusan tahun tersembunyi dalam peradaban Barat, narasi lain yang tidak pernah diceritakan dalam sejarah kemanusiaan, Der verborgene Widerspruch in der Geschichte der Menschheit.
“Die Weltgeschichte ist nicht der Boden des Glücks. Die Perioden des Glücks sind leere Blätter in ihr,” kata Hegel dalam Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Sejarah dunia bukanlah medan kebahagiaan. Masa-masa bahagia adalah lembaran-lembaran sejarah yang kosong.
Dengan merujuk kepada perdamaian di Flanders, 1914, kebanyakan sejarah berbicara tentang perang. Perang dunia pertama berlangsung selama 1568 hari; tetapi perdamaian hanya terselip sejenak – tidak mencapai 24 jam – pada malam dan hari Natal. Yang besar adalah perang. Yang kecil adalah perdamaian.
Usai hari Natal bersama, mereka melanjutkan lagi peperangan. Empat tahun kemudian, ketika api perang sudah padam dan langit Eropa cerah kembali, lebih dari delapan juta orang dibantai di medan-medan pertempuran di Eropa. Korban ini disusul dengan jutaan korban karena penyakit. Perang dunia pertama mempermalukan Eropa sebagai pembawa obor pencerahan. Menurut penulis A.A. Milne, ini adalah “degradasi yang mengecilkan kebejatan binatang, kegilaan yang mempermalukan semua rumah orang gila”.
Pada abad XVII, Thomas Hobbes, filusuf dan dianggap pendiri filsafat politik, membaca buku Sejarah Perang Pelopponesia, ditulis oleh Jendral dan sejarawan Athena- Thucydides. Ia serasa mendapat pencerahan tentang mengapa perang berlangsung lama, dan menimbulkan korban-korban yang mengerikan. Menurut Thucydides, perang terjadi karena ledakan wabah penyakit istimewa; yakni, wabah “human nature”. Human nature meledak karena tidak dikendalikan oleh kekuatan besar. “Tabiat manusia yangs selalu melawan hukum, dan sekarang melawan Tuannya, dengan senang mempertontonkan emosi yang tak terkendali, tidak menghormati keadilan, dan menjadi musuh dari semua pemegang otoritas.” Thucydides selanjutnya menulis, “Penyebab dari semua kejahatan adalah nafsu kekuasaaan yang muncul dari kerakusan dan ambisi, dan dari gairah ini muncul tindakan kekerasan dari semua pihak yang bertikai.”
Tahun 1628 Hobbes menerjemahkan perang Pelopponesia dan memuji Thucydides setengah mati. Dalam otobiografinya, Hobbes menulis:
Deangan paragraf itu, Jeremy Rifkin memulai bukunya tentang peradaban empatis. Sangat dramatis. Untuk selanjutnya saya tuliskan kembali kisah yang terkenal sebagai Perdamaian Natal, Christmas truce, Weihnachtsfrieden atau Trêve de Noël.
Malam Natal membungkus bumi, dan langit menaburkan butir-butir salju. Parit-parit perlahan-lahan dipenuhi air dan lumpur. Suasana mencekam. Seperti biasa, malam Natal mengingatkan mereka pada orang-orang yag dikasihi, yang ditinggalkan di kampung halamannya. Sebagian di antara prajurit ada yang membuka-buka surat atau hadiah Natal yang dikirimkan ke front.
Pasukan Inggris dan Perancis di Front Barat tiba-tiba dikejutkan senandung yang bermula pelan-pelan, kemudian makin lama makin keras, diikuti oleh orang yang makin lama makin banyak, dari arah pasukan Jerman. Liriknya dalam bahasa Jerman, tetapi lagunya dikenal oleh semua orang. “Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht”. Dari arah pasukan Jerman. Bibir-bibir mereka tanpa terasa menggumamkan lagu itu dengan lirik dalam bahasa masing-masing. Makin lama makin keras. Ketika mata-mata prajurit Inggris diarahkan ke lingkaran parit Jerman, mereka melihat pohon-pohon Natal kecil berkelip-kelip sepanjang lingkaran parit. “Seperti untaian tasbih,” kata seorang prajurit Inggris. Hampir tak terasa, airmata mereka mengalir membasahi pipi, menghangatkan kebekuan karena percik-percik hujan salju di muka mereka.
Dari dalam parit kedua belah pihak menyembul kepala-kepala berani. Biasanya kepala-kepala yang muncul disambut dengan tembakan sniper. Kali ini, bukan tembakan yang menyertai kepala-kepala itu, tapi kalimat Inggris dengan aksen Jerman. “Merry Xmas! Merry Xmas!” dibalas dengan kalimat yang sama oleh tentara Inggris dan Joyeux Noelle oleh tentara Perancis. Tubuh-tubuh yang kecapean sekarang sudah berada di tanah lapang tak bertuan.
“My Name is James“
“Ich heisse Otto”
Mereka berjabatan tangan, diikuti oleh ratusan, bahkan ribuan orang. Menurut Wikipedia, sekitar 100.000 tentara Inggris dan Jerman terlibat dalam gencatan senjata tidak resmi; dan tidak disetujui oleh para perwira atasan mereka. Mereka yang beberapa jam sebelumnya saling membunuh sekarang bersalaman. Muka-muka beringas sekarang menunjukkan keramahan. Mereka bernyanyi bersama, saling bercanda, bertukar hadiah, barbagi kenangan. Mereka menyanyikan Christmas Carol ketika bertemu dan sebelum berpisah mereka menyanyikan “Auld Lang Syne”
Henry Williamson, waktu itu prajurit berusia 19 tahun, menulis surat pada ibunya:
“Mama tersayang, aku menulis dari parit perang. Sekarang jam 11 pagi. Di sampingku ada pelita minyak, di depanku galian yang basah dengan jerami di dalamnya. Tanah di bawahku licin dalam parit yang sebenarnya, tetapi di mana-mana beku. Di mulutku ada pipa hadiah dari Princess Mary. Dalam pipaku ada tembakau. Tentu saja, pasti begitu kata Mama. Tapi sebentar. Dalam pipa ini ada tembakau Jerman. Haha, pasti kata Mama lagi, diambil dari tawanan Jerman atau ditemukan dari parit musuh yang direbut. Bukan, Mama sayang. Dari prajurit Jerman. Benar, prajurit Jerman dibawa dari paritnya sendiri. Kemarin orang Inggris dan orang Jerman bertemu, bersalaman di lapangan di antara parit-parit, berbagi suvenir, dan bersalaman. Ya, sepanjang hari Natal dan pada waktu aku menulis surat ini. Marvellous, isn’t it? Indah nian, bukan?”
Itulah perdamaian kecil dalam perang besar di front sebelah barat, 1914, ketika Jerman, Perancis, dan Inggris, bersama-sama merayakan Hari Natal. Kalimat barusan sebetulnya terjemahan dari judul buku yang sangat panjang ditulis Michael, Jürgs (2005), Der kleine Frieden im Großen Krieg: Westfront 1914: als Deutsche, Franzosen und Briten gemeinsam Weihnachten feierten. München.
Menurut Rifkin, perdamaian kecil ini mengungkapkan “hakikat” kemanusiaan yang selama ratusan tahun tersembunyi dalam peradaban Barat, narasi lain yang tidak pernah diceritakan dalam sejarah kemanusiaan, Der verborgene Widerspruch in der Geschichte der Menschheit.
“Die Weltgeschichte ist nicht der Boden des Glücks. Die Perioden des Glücks sind leere Blätter in ihr,” kata Hegel dalam Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Sejarah dunia bukanlah medan kebahagiaan. Masa-masa bahagia adalah lembaran-lembaran sejarah yang kosong.
Dengan merujuk kepada perdamaian di Flanders, 1914, kebanyakan sejarah berbicara tentang perang. Perang dunia pertama berlangsung selama 1568 hari; tetapi perdamaian hanya terselip sejenak – tidak mencapai 24 jam – pada malam dan hari Natal. Yang besar adalah perang. Yang kecil adalah perdamaian.
Usai hari Natal bersama, mereka melanjutkan lagi peperangan. Empat tahun kemudian, ketika api perang sudah padam dan langit Eropa cerah kembali, lebih dari delapan juta orang dibantai di medan-medan pertempuran di Eropa. Korban ini disusul dengan jutaan korban karena penyakit. Perang dunia pertama mempermalukan Eropa sebagai pembawa obor pencerahan. Menurut penulis A.A. Milne, ini adalah “degradasi yang mengecilkan kebejatan binatang, kegilaan yang mempermalukan semua rumah orang gila”.
Pada abad XVII, Thomas Hobbes, filusuf dan dianggap pendiri filsafat politik, membaca buku Sejarah Perang Pelopponesia, ditulis oleh Jendral dan sejarawan Athena- Thucydides. Ia serasa mendapat pencerahan tentang mengapa perang berlangsung lama, dan menimbulkan korban-korban yang mengerikan. Menurut Thucydides, perang terjadi karena ledakan wabah penyakit istimewa; yakni, wabah “human nature”. Human nature meledak karena tidak dikendalikan oleh kekuatan besar. “Tabiat manusia yangs selalu melawan hukum, dan sekarang melawan Tuannya, dengan senang mempertontonkan emosi yang tak terkendali, tidak menghormati keadilan, dan menjadi musuh dari semua pemegang otoritas.” Thucydides selanjutnya menulis, “Penyebab dari semua kejahatan adalah nafsu kekuasaaan yang muncul dari kerakusan dan ambisi, dan dari gairah ini muncul tindakan kekerasan dari semua pihak yang bertikai.”
Tahun 1628 Hobbes menerjemahkan perang Pelopponesia dan memuji Thucydides setengah mati. Dalam otobiografinya, Hobbes menulis:
Homer and Vewil, Horace, Sophocles,
Plautus, Euripides, Aristophanes,
I understood, nay more; but of all these
There's none that pleas'd me like Thucydides.
He says Democracy's a Foolish Thing,
Than a Republick Wiser is one King
Ada penulis yang mebahas konsep manusia dari Thucydides sangat Hobbesian. Yang lebih tepat ialah mengatakan bahwa konsep manusia Hobbes sangat Trhucydidesian. Homo homini lupus. Bellum omnium contra omnes. Tabiat manusia adalah melakukan apa pun untuk kepentingan sendiri, untuk menjadi serigala bagi manusia lain. Cerita manusia adalah cerita tentang semua memerangi semua.
Pada Bab XIII kitab Leviathan, Hobbes menyebutkan “a generall inclination of all mankind, a perpetuall and restless desire of power after power that ceaseth only in death.” Pada Bab XVII, Hobbes bertanya mengapa manusia tidak bisa hidup rukun seperti semut dan lebah. Ia menjawab sendiri, karena manusia “continually in competition for honor and dignity.” Kompetisi ini sejatinya adalah kompetisi untuk kekuasaan.
“The easiest way to obtain glory, is to obtain power,” kata Bertrand Russell. Kata Russell, the desire for glory dan the desire for power sama saja. Menurut Raymond Aron, negara “tidak berusaha untuk kuat buat mencegah agresi dan menikmati perdamaian; negaraa berusaha kuat agar ditakuti, dihormati, atau dikagumi.” “Libido dominandi, “kata Santo Agustinus, “menjadikan manusia lebih buruk dari binatang dalam hal kekejamannya.”
“Ular boa pembelit seudah makan langsung tidur sampai seleranya muncul lagi, “kata Russell, “tetapi kehausan akan kekuasaan dan kebesaran pada manusia hanya dibatasi oleh kemungkinan yang dibayangkan oleh imajinasinya.” Mengapa manusia selalu mengejar kebesaran dan kekuasaan? Karena satu-satunya motif yang menggerakkan manusia adalah der Wille zur Macht, menurut Nietzsche. Der Wille zur Macht adalah juga der Wille zum Leben. Dalam Beyond Good and evil, Nietzsche menulis, physiologist shluld think again before postulating the drive to self preservation as the cardinal drive in an organic being. A living thing desires above all to vent its strength-life as such is will to power.” Morgenthau, melanjutkan Nietzsche, menegaskan “man is born to seek power” dan “aspires towr exrcising political dominationover others” Kekuasaan adalah “elemntal bio-psychological drive” semacam instink untuk hidup atau reproduksi.
Saya dapat mengutip banyak sekali para pemikir yang menganggap bahwa tabiat manusia itu mementingkan diri sendiri, mengejar mimpinya bukan saja tanpa peduli sama orang lain, tetapi bahkan dengan mengorbankan orang lain. Dari John Adams, Machiavelli, Jeremy Bentham, Charles Darwin, sampai selfish gene-nya Richard Dawkins dan need for power-nya David MaClelland. Tetapi makalah ini menjadi terlalu panjang. Saya hanya ingin menyimpulkan bahwa pandangan manusia sebagai homo agresivus, telah menjadi pandangan hidup Barat yang dominan selama dua milenium. Sekarang homo agresivus digunakan untuk menjelasakan bukan saja filsafat manusia, tapi juga pandangan tentang manusia dalam ekonomi, politik, antropologi, biologi, dan telaah sains lainnya.
Marshall Sahlins menyebutnya The Western Illusion of Human Nature. Dalam bukunya dengan judul tersebut, ia menulis “For more than two millennia, the peoples we call “Western” have been haunted by the specter of their own inner being: an apparition of human nature so avaricious and contentious that, unless it is somehow governed, it will reduce society to anarchy.”
Walhasil, perang dunia pertama dan perang-perang lainnya, baik sesudahnya maupun sebelumnya, dapat dijelaskan dengan homo agresivus. Lalu, apa yang bisa menjelaskan Chritsmas truce pada malam dan hari Natal 1914. Homo agresivus tidak laku di sini. Homo agresivus juga tidak bisa menjelaskan altruisme, ketika orang mengurbankan dirinya bagi kepentingan orang lain -Schindler yang menyelamatkan ribuan Yahudi dengan memposisikan dirinya dalam bahaya pada pemerintahan Nazi untuk peristiwa yang spektakuler atau orang-orang yang memberikan ginjalnya kepada orang lain yang bahkan tidak dikenalnya, dokter-dokter yang meninggalkan kariernya dan memilih bertugas di daerah yang berbahaya, atau tukang-tukang pikul yang bekerja di ibu kota -dibakar terik mentari digoreng derita tak terperi dan menyerahkan sepenuh hasilnya untuk keluarga di kampung.
“Orang-orang yang berkumpul di Flanders mengungkapkan sensibilitas manusia yang paling mendalam -sensibilitas yang memancar dari inti eksistensi manusia yang melintas portal waktu dan situasi apa pun yang tengah terjadi. Kita hanya perlu bertanya kepada diri sendiri mengapa kita merasa terharu menyaksikan apa yang mereka lakukan. Mereka memilih untuk menjadi manusias. Kualitas manusiawi utama yang nereka ungkapkan adalah empati pada sesama.” Tulis Jeremy Rifkin.
Bukan tempatnya di sini untuk meperdebatkan makna atau definisi empati. Kita bisa berdebat tentang apa itu manusia berjam-jam atau berjilid-jilid, tapi saya segera tahu bahwa Anda manusia. Begitu pula empati. Apa yang terjadi di Flanders adalah empati. Ketika tetua Indian di Amerika Utara berkata: Walk a mile in his moccasin, ia mengajarkan empati. Saya kutipkan dua bait puisi Mary T. Lathrap tentang makna petuah Indian itu:
Pada Bab XIII kitab Leviathan, Hobbes menyebutkan “a generall inclination of all mankind, a perpetuall and restless desire of power after power that ceaseth only in death.” Pada Bab XVII, Hobbes bertanya mengapa manusia tidak bisa hidup rukun seperti semut dan lebah. Ia menjawab sendiri, karena manusia “continually in competition for honor and dignity.” Kompetisi ini sejatinya adalah kompetisi untuk kekuasaan.
“The easiest way to obtain glory, is to obtain power,” kata Bertrand Russell. Kata Russell, the desire for glory dan the desire for power sama saja. Menurut Raymond Aron, negara “tidak berusaha untuk kuat buat mencegah agresi dan menikmati perdamaian; negaraa berusaha kuat agar ditakuti, dihormati, atau dikagumi.” “Libido dominandi, “kata Santo Agustinus, “menjadikan manusia lebih buruk dari binatang dalam hal kekejamannya.”
“Ular boa pembelit seudah makan langsung tidur sampai seleranya muncul lagi, “kata Russell, “tetapi kehausan akan kekuasaan dan kebesaran pada manusia hanya dibatasi oleh kemungkinan yang dibayangkan oleh imajinasinya.” Mengapa manusia selalu mengejar kebesaran dan kekuasaan? Karena satu-satunya motif yang menggerakkan manusia adalah der Wille zur Macht, menurut Nietzsche. Der Wille zur Macht adalah juga der Wille zum Leben. Dalam Beyond Good and evil, Nietzsche menulis, physiologist shluld think again before postulating the drive to self preservation as the cardinal drive in an organic being. A living thing desires above all to vent its strength-life as such is will to power.” Morgenthau, melanjutkan Nietzsche, menegaskan “man is born to seek power” dan “aspires towr exrcising political dominationover others” Kekuasaan adalah “elemntal bio-psychological drive” semacam instink untuk hidup atau reproduksi.
Saya dapat mengutip banyak sekali para pemikir yang menganggap bahwa tabiat manusia itu mementingkan diri sendiri, mengejar mimpinya bukan saja tanpa peduli sama orang lain, tetapi bahkan dengan mengorbankan orang lain. Dari John Adams, Machiavelli, Jeremy Bentham, Charles Darwin, sampai selfish gene-nya Richard Dawkins dan need for power-nya David MaClelland. Tetapi makalah ini menjadi terlalu panjang. Saya hanya ingin menyimpulkan bahwa pandangan manusia sebagai homo agresivus, telah menjadi pandangan hidup Barat yang dominan selama dua milenium. Sekarang homo agresivus digunakan untuk menjelasakan bukan saja filsafat manusia, tapi juga pandangan tentang manusia dalam ekonomi, politik, antropologi, biologi, dan telaah sains lainnya.
Marshall Sahlins menyebutnya The Western Illusion of Human Nature. Dalam bukunya dengan judul tersebut, ia menulis “For more than two millennia, the peoples we call “Western” have been haunted by the specter of their own inner being: an apparition of human nature so avaricious and contentious that, unless it is somehow governed, it will reduce society to anarchy.”
Walhasil, perang dunia pertama dan perang-perang lainnya, baik sesudahnya maupun sebelumnya, dapat dijelaskan dengan homo agresivus. Lalu, apa yang bisa menjelaskan Chritsmas truce pada malam dan hari Natal 1914. Homo agresivus tidak laku di sini. Homo agresivus juga tidak bisa menjelaskan altruisme, ketika orang mengurbankan dirinya bagi kepentingan orang lain -Schindler yang menyelamatkan ribuan Yahudi dengan memposisikan dirinya dalam bahaya pada pemerintahan Nazi untuk peristiwa yang spektakuler atau orang-orang yang memberikan ginjalnya kepada orang lain yang bahkan tidak dikenalnya, dokter-dokter yang meninggalkan kariernya dan memilih bertugas di daerah yang berbahaya, atau tukang-tukang pikul yang bekerja di ibu kota -dibakar terik mentari digoreng derita tak terperi dan menyerahkan sepenuh hasilnya untuk keluarga di kampung.
“Orang-orang yang berkumpul di Flanders mengungkapkan sensibilitas manusia yang paling mendalam -sensibilitas yang memancar dari inti eksistensi manusia yang melintas portal waktu dan situasi apa pun yang tengah terjadi. Kita hanya perlu bertanya kepada diri sendiri mengapa kita merasa terharu menyaksikan apa yang mereka lakukan. Mereka memilih untuk menjadi manusias. Kualitas manusiawi utama yang nereka ungkapkan adalah empati pada sesama.” Tulis Jeremy Rifkin.
Bukan tempatnya di sini untuk meperdebatkan makna atau definisi empati. Kita bisa berdebat tentang apa itu manusia berjam-jam atau berjilid-jilid, tapi saya segera tahu bahwa Anda manusia. Begitu pula empati. Apa yang terjadi di Flanders adalah empati. Ketika tetua Indian di Amerika Utara berkata: Walk a mile in his moccasin, ia mengajarkan empati. Saya kutipkan dua bait puisi Mary T. Lathrap tentang makna petuah Indian itu:
Pray, don’t find fault with the man that limps,
Or stumbles along the road.
Unless you have worn the moccasins he wears,
Or stumbled beneath the same load.
Just walk a mile in his moccasins
Before you abuse, criticize and accuse.
If just for one hour, you could find a way
To see through his eyes, instead of your own muse
Itulah empati.
Pada abad ke-13, hidup orang bijak dari Persia. Namanya Sa’di. Ia mengajarkan agama dengan cerita dan puisi. Delapan ratus tahun setelah kematiannya, salah satu puisinya disegarkan kembali, diabadikan pada salah satu jalan masuk ke Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa:
Pada abad ke-13, hidup orang bijak dari Persia. Namanya Sa’di. Ia mengajarkan agama dengan cerita dan puisi. Delapan ratus tahun setelah kematiannya, salah satu puisinya disegarkan kembali, diabadikan pada salah satu jalan masuk ke Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa:
Anak-anak Adam adalah anggota-anggota satu badan
Dari jauhar tunggal di alam azali diciptakan
Jika salah satu anggota ditimpa penderitaan
Anggota yang lain tak kan tenang bertahan
Jika kamu tak mampu berempati pada derita liyan
Tidak layak disematkan padamu nama sang insan
“Tu kaz mehnat-e digaraan bi ghami”, jika kamu tidak berduka melihat derita liyan, saya terjemahkan sebagai tidak mampu berempati. Mungkin karena itulah, para pendiri gedung PBB memetik puisi Sa’di. Bangsa-bangsa yang berkumpul di PBB bertekad untuk menegakkan dunia baru berdasarkan empati. Bukan dunia yang bergerak di atas prinsip Hobbes – homo homini lupus, manusia serigala bagi manusia yang lain; bukan dunia yang berputar berdasarkan teori Darwin- the survival of the fittest, hanya yang kuat yang hidup; bukan dunia yang beraksi mengikuti thanatos Freud – dorongan untuk menyerang dan menghancurkan; bukan pula dunia yang bergelut dalam pasar bebas Smith- ketika setiap orang hanya berjuang untuk kepentingannya sendiri.
Renungkan puisi Sa’di. Itulah empati.
Empati ditelantarkan orang pada abad 20; abad introspeksionisme. Abad 21 adalah abad empati – abad outrospeksionisme. Kini kajian filsafat -sejak penafsiran empati Heidegger sampai pembahasan Husserl tentang intensionalitas empatik - dan berbagai penelitian ilmiah – sejak psikoanalisis sampai ke nerosains- menarik perhatian kita kepada empati. Empati diteliti dalam psikologi sosial, sosiologi, primatologi, neurosains, psikiatri, dan bahkan …. marketing.
Hubungan Empatik
Pada momen sekarang ini, walaupun terlambat, saya ingin membicarakan empati dalam hubungan antar umat beragama (juga intra). Ada dua hubungan: agresif dan empatik. Umat Kristiani -yang sedang berperang- menyembulkan kepalanya, menantang tembakan karena disentuh lagu Natal. Di sini agama melahirkan hubungan empatik.
Jeremy Young dalam The Cost of Certainty mengatakan bahwa struktur teologi Kristiani mendukung rekor kekerasan yang mengerikan, persekusi, kebencian, intoleransi, stereotip, abuse, dan hipokrisi. Saya dan saudara-saudara -tanpa harus mengutip buku- menyaksikan bahwa teologi kelompok jihad -termasuk FPI, ISIS, HTI- adalah teologi yang melahirkan relasi agresif. Di sini hubungan agama agresif.
Apa yang terjadi dalam relasi umat beragama yang agresif?
Renungkan puisi Sa’di. Itulah empati.
Empati ditelantarkan orang pada abad 20; abad introspeksionisme. Abad 21 adalah abad empati – abad outrospeksionisme. Kini kajian filsafat -sejak penafsiran empati Heidegger sampai pembahasan Husserl tentang intensionalitas empatik - dan berbagai penelitian ilmiah – sejak psikoanalisis sampai ke nerosains- menarik perhatian kita kepada empati. Empati diteliti dalam psikologi sosial, sosiologi, primatologi, neurosains, psikiatri, dan bahkan …. marketing.
Hubungan Empatik
Pada momen sekarang ini, walaupun terlambat, saya ingin membicarakan empati dalam hubungan antar umat beragama (juga intra). Ada dua hubungan: agresif dan empatik. Umat Kristiani -yang sedang berperang- menyembulkan kepalanya, menantang tembakan karena disentuh lagu Natal. Di sini agama melahirkan hubungan empatik.
Jeremy Young dalam The Cost of Certainty mengatakan bahwa struktur teologi Kristiani mendukung rekor kekerasan yang mengerikan, persekusi, kebencian, intoleransi, stereotip, abuse, dan hipokrisi. Saya dan saudara-saudara -tanpa harus mengutip buku- menyaksikan bahwa teologi kelompok jihad -termasuk FPI, ISIS, HTI- adalah teologi yang melahirkan relasi agresif. Di sini hubungan agama agresif.
Apa yang terjadi dalam relasi umat beragama yang agresif?
- Agama melakukan dehumanisasi. Satu kelompok agama diberi gelar-gelar atau label-label yang menghilangkan sifat-sifat kemanusiannya. Mereka dipanggil sebagai anggota bonbin: monyet, kutu, anjing-anjing neraka. Mereka diberi sifat-sifat yang menjijikkan tetapi mengancam: sesat, kafir, anak zinah, pembohong dan sebagainya.
- Agama dijadikan alat untuk merebut kekuasaan. Setiap upaya untuk merebut kekuasaan selalu machiavellian. Tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan sekarang tujuan menghalalkan darah dan kehormatan. Agama disebarkan di atas dasar otoritas elit agama. Elit agama dijadikan wakil Tuhan di bumi.
- Agama membentuk jarak -jarak geografis, psikologis, dan sosial- di antara kami dengan liyan. Dalam teologi kelompok radikal, membangun jarak ini disebut hijrah.
*) Disampaikan pada Halaqah Damai XXII, Rabu, 25 September 2019 di Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan, yang dilaksanakan oleh Religious Sacre Coeur de Jesu (RSCJ) Indonesia, UNPAR dan PP IJABI




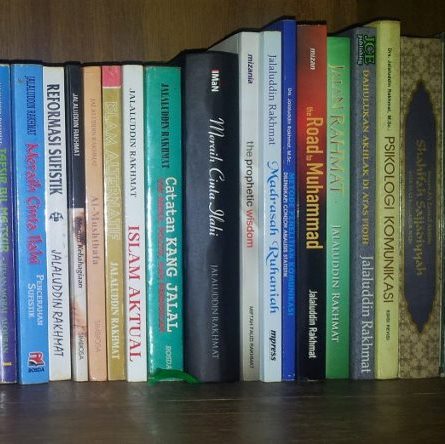
 RSS Feed
RSS Feed
